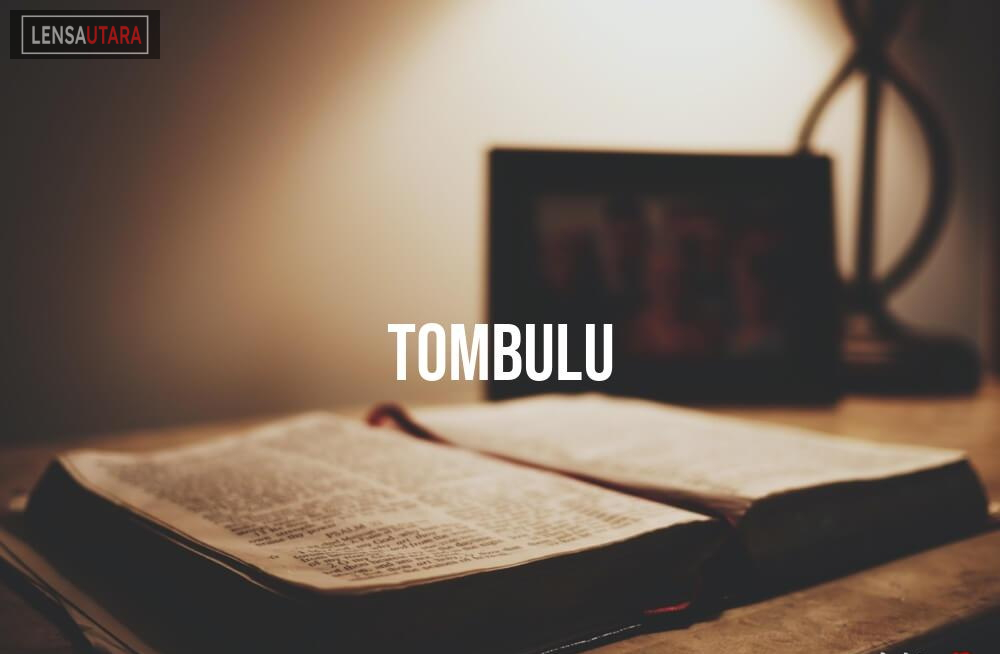Kehidupan tidak berasal dan berlanjut karena saling menghisap atau memperdayakan. Kesejahteraan tidak hanya untuk sekelompok orang yang memegang kuasa keagamaan atau politik. Kebersamaan adalah daya untuk membebaskan setiap orang dari ketidakberdayaan secara spiritual dan material.
Jadi, mestinya “pangucapan syukur” mengingatkan orang-orang Minahasa tentang daya “mapalus” (kebersamaan), tentang pemberian dari Opo Wailan Wangko yang dihayati sebagai berkat. Dan tentang arti menjadi manusia religius yang sekaligus sosial dalam kesatuan dengan semesta.
Itulah sehingga praktik “pangucapan syukur” identik dengan “dapur-dapur berasap” dari rumah-rumah anggota komunitas tanda sedang bersiap untuk berpartisipasi pada ritual kehidupan, yang oleh gereja mengubahnya terpusat di gedung gereja. Ibadah itu tidak terpisah dengan berbagi bersama orang lain melalui jamuan pesta makan.
Bagaimana mungkin tradisi atau praktik kultural yang kaya makna itu kemudian hanya ditandai dalam bentuk “amplop”. Atau pula, sungguh adalah suatu cara berteologi yang munafik, ketika hari ini masih saja terdengar khotbah dari para pendeta di atas mimbar yang mengutuk warisan-warisan praktik agama leluhur mereka sebagai yang harus ditolak atau diperangi. Selain itu, sungguh ini adalah ciri cara beragama yang munafik, tapi juga durhaka terhadap leluhur dan kebudayaannya sendiri.
Pesta “pangucapan syukur” tetaplah ia sebagai “ritual” kehidupan yang nilai dasarnya adalah penghayatan secara spiritual tentang kehidupan sebagai berkat dari Yang Ilahi melalui semesta. Pesta, makan bersama, saling bersua antara keluarga, kegembiraan dan keramaian wanua/roong adalah ekspresi syukur yang khas Minahasa.
Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan.